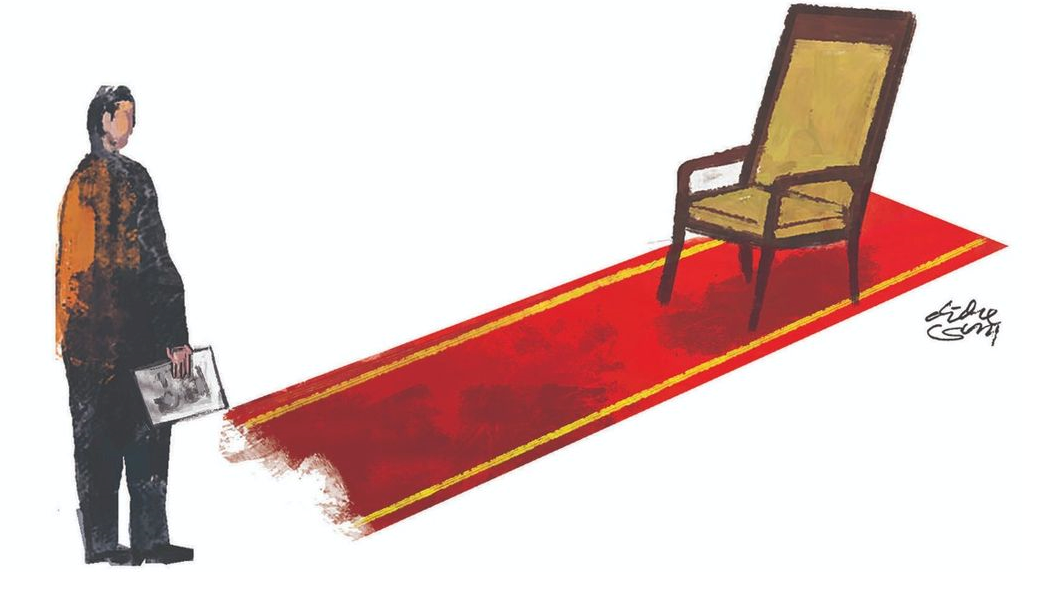Keadilan Restoratif, Tepatkah untuk Koruptor?
Wacana penerapan keadilan restoratif melalui pengembalian seluruh hasil korupsi beserta keuntungan yang diperoleh dengan jumlah yang dilipatgandakan akan menimbulkan suatu kekhawatiran. Mengapa demikian ?
Oleh
HUMPHREY DJEMAT
4 Januari 2023 04:30 WIB · 7 menit baca
HERYUNANTO
Ilustrasi
Dr Johanis Tanak, mantan jaksa yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Lili Pintauli Siregar menjadi Wakil Ketua KPK 2019-2023, saat seleksi di DPR mengusulkan penerapan keadilan restoratif bagi pelaku korupsi.
Caranya, menurut Johanis, dengan pengembalian uang dengan jumlah dua atau tiga kali lipat dari nilai yang dikorupsi. Dengan adanya pengembalian itu, pelaku tidak perlu diproses hukum. Ditambahkan, usulan ini nantinya harus dituangkan dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.
Usulan itu juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pasal 3 Peraturan BPK No 2/2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang pada pokoknya apabila BPK menemukan kerugian keuangan negara dan temuan itu dikembalikan dalam tempo 60 hari, proses tindak pidana tidak dilakukan.
Selama ini keadilan restoratif (restorative justice) dikenal sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak-pihak lain untuk mencari penyelesaian secara adil, yaitu adanya pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana.
Dengan adanya pengembalian itu, pelaku tidak perlu diproses hukum.
Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan oleh Kepolisian Negara RI (Polri) melalui Peraturan Kepala Polri (Perkap) No 6/2019 yang kemudian diperluas dan diatur secara khusus melalui Perkap No 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap ini memuat ketentuan tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan melalui penyelesaian keadilan restoratif.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) No 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui perja ini dimungkinkan penghentian penuntutan untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Syaratnya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tak lebih dari 5 tahun, dan barang bukti atau nilai kerugian tak lebih dari Rp 2,5 juta.
Respons masyarakat terhadap pendekatan keadilan restoratif juga positif. Terbukti, berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 83 persen masyarakat setuju dengan penegak hukum yang lebih mengedepankan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan (Kompas, 14/2/2022).
Namun, bagaimana halnya jika keadilan restoratif diterapkan untuk kasus korupsi?
Infografik Dukungan Publik untuk Keadilan Restoratif
Tidak mudah diterapkan di Indonesia
Meski secara yuridis pembuat UU dapat menyusun berbagai ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam berbagai kasus tindak pidana, secara teoretis wacana keadilan restoratif tidak dapat diterapkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime), khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dalam UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang kemudian diubah menjadi UU No 20/2001, korupsi secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan yang terjadi secara sistematik dan meluas yang akibatnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Wacana penerapan keadilan restoratif melalui pengembalian seluruh hasil korupsi beserta keuntungan yang diperoleh dengan jumlah yang dilipatgandakan akan menimbulkan suatu kekhawatiran. Mengapa? Sebab, akan lahir stigma publik bahwa Indonesia menghalalkan praktik korupsi.
Sebab, akan lahir stigma publik bahwa Indonesia menghalalkan praktik korupsi.
Selain itu, hal ini juga dikhawatirkan akan mendorong terjadi perhitungan ekonomis atau hitung-hitungan secara matematis ketika seseorang berniat melakukan praktik korupsi. Belum lagi jika ternyata nilai kerugian negara dan keuntungan yang didapatkan si pelaku korupsi diperoleh secara tidak akurat.
Perlu diingat pula bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan timbulnya kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh si pelaku atas perbuatan korupnya, tetapi juga terdapat pihak-pihak lain yang telah diuntungkan. Selain itu, terdapat juga dampak kerugian dan luka yang dirasakan oleh masyarakat luas yang menjadi pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan korupsi tersebut.
Walaupun ada pengembalian seluruh hasil korupsi beserta keuntungan oleh si pelaku korupsi dengan jumlah yang dilipatgandakan, pengembalian itu hanya menghapuskan kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh si pelaku.
Pengembalian itu tak menghapus perbuatan melawan hukum si pelaku korupsi dan keuntungan yang diperoleh pihak-pihak lain atas perbuatan si pelaku korupsi atau menghapus ”luka” masyarakat akibat korupsi. Misalnya, dampak dari korupsi di proyek Hambalang menyebabkan pembangunan fasilitas olahraga tidak bisa digunakan dan dinikmati masyarakat sama sekali hingga kini.
Pencegahan masih lemah
Hasil survei Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia 2022 oleh Badan Pusat Statistik yang dirilis awal Agustus lalu, terdapat kenaikan IPAK 0,05 poin dari skor 3,88 pada 2021 menjadi 3,93 pada 2022.
Dengan kenaikan 0,05 poin ini, IPAK tahun ini masih jauh di bawah target. Ini sekaligus memperlihatkan adanya masalah mendasar sehingga sikap antikorupsi masyarakat tak menguat signifikan. Salah satunya sikap masyarakat yang dinilai kian permisif pada perilaku korupsi (Kompas, 2/8/2022).
Menyikapi hal ini, pemberantasan korupsi harus terus digalakkan dengan strategi atau sistem yang harus dititikberatkan pada pencegahan terhadap perilaku korupsi secara masif, tidak terbatas pada pencegahan korupsi oleh KPK saat ini.
Ini, antara lain, dilakukan melalui pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, serta menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
Salah satu faktor penyebab masih tingginya korupsi di Indonesia adalah tidak adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan menindak para terduga korupsi secara masif.
Pencegahan melalui pembuktian terbalik
Upaya pencegahan oleh KPK saat ini dirasa belum dapat menekan tingkat korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi harus digalakkan melalui strategi pencegahan, terutama dengan cara memegang teguh nilai-nilai integritas pribadi yang kemudian ditularkan secara meluas ke orang lain.
Langkah itu diharapkan bisa mewujudkan negara dengan tingkat korupsi rendah. Jika semua lini masyarakat semangat berperilaku antikorupsi, sinergi berikutnya adalah dengan penegakan hukum yang baik.
Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum. Yang juga penting adalah, pengawasan oleh setiap individu, baik yang berada di kementerian, lembaga, organisasi pemerintah, maupun swasta, untuk mendeteksi dan menindak para terduga pelaku korupsi.
Salah satu faktor penyebab masih tingginya korupsi di Indonesia adalah tidak adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan menindak para terduga korupsi secara masif. Cara yang efektif adalah dengan menciptakan suatu instrumen hukum yang memberikan hak kepada seluruh masyarakat menjadi perpanjangan ”tangan” penegak hukum, khususnya KPK.
Peraturan Pemerintah No 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pernah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo dirasa belum cukup efektif.
Sudah sepatutnya terdapat suatu instrumen hukum yang dibuat sesederhana mungkin. Yakni dengan membuka suatu sistem pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan praktik korupsi yang didasarkan pada kontrol/ pengawasan dari masyarakat yang dilakukan secara kasatmata terhadap cara hidup seseorang yang dinilai atau dirasa tidak sesuai dengan jabatan atau profesi orang itu.
Dengan cara ini, di antara masyarakat akan terdapat budaya saling mengawasi.
Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah netizen yang ramai-ramai menyoroti perilaku pejabat yang kerap tampil berpakaian dan/atau menggunakan jam tangan, sepatu, atau tas dengan merek mewah. Dari situ, tidak dapat disalahkan jika kemudian timbul dugaan korupsi oleh orang dengan jabatan tersebut.
Masyarakat harus diberikan hak dan peluang seluas-luasnya untuk mengajukan pengaduan yang bersifat rahasia. Pengaduan ini kemudian diikuti dengan komitmen dari penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pengaduan itu tanpa pandang bulu. Caranya dengan melakukan penelusuran dan secara langsung menerapkan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada pihak teradu untuk membuktikan asal-usul atas obyek pengaduan.
Apabila pihak yang diadukan tak dapat membuktikan bahwa asal-usul perolehan dari obyek pengaduan bukanlah dari hasil korupsi, aparat penegak hukum harus melakukan penindakan lanjutan dengan melakukan proses hukum terhadap si terduga pelaku korupsi.
Pengawasan ini tentunya tidak hanya dibatasi pada seseorang yang diduga berbuat korupsi, tetapi juga terbuka bagi anggota keluarga dari seorang pejabat ataupun pihak swasta lainnya yang cara hidupnya dinilai atau dilihat secara kasatmata tak sesuai dengan cara hidup dan kemampuannya sehari-hari.
Eksistensi pengawasan masyarakat sesungguhnya tersirat dalam instruksi Presiden yang disampaikan kepada pejabat Polri di Istana Negara, 14 Oktober lalu.
Masyarakat harus diberikan hak dan peluang seluas-luasnya untuk mengajukan pengaduan yang bersifat rahasia.
Ketika itu, jajaran Polri dan pejabat lainnya diingatkan agar berhati-hati dengan gaya hidup mereka dalam situasi ekonomi yang sulit agar tidak terjadi letupan-letupan akibat kecemburuan sosial-ekonomi sebagai dampak dari gaya hidup mereka. Terlebih, di era media sosial dewasa ini, masyarakat bisa leluasa menyoroti tingkah laku para pejabat hingga detail.
Sistem pencegahan yang melibatkan pengawasan masif dari semua lapisan masyarakat serta disertai adanya sistem pembuktian terbalik dipastikan akan menimbulkan kegelisahan pada setiap orang yang berperilaku koruptif.
Namun, semua itu juga membutuhkan komitmen, political will, serta keberanian pemerintah dan publik untuk menyusun instrumen hukum yang menuntut standar etik dan norma yang lebih tinggi pada setiap warga. Juga kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak sendi-sendi kebangsaan. Dari sana kemudian diharapkan juga muncul ”budaya malu korupsi”.
Humphrey Djemat Advokat dan Chairman pada Kantor Gani Djemat & Partners
KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)
Humphrey Djemat
Editor:
SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN
Humphrey Djemat Image widget